Tulisan ini pernah dimuat di Majalah La'at Natas (Buletin Para Frater SVD Asal Provinsi SVD Ruteng) edisi Januari-Juni 2018.
Ferdi Jehalut
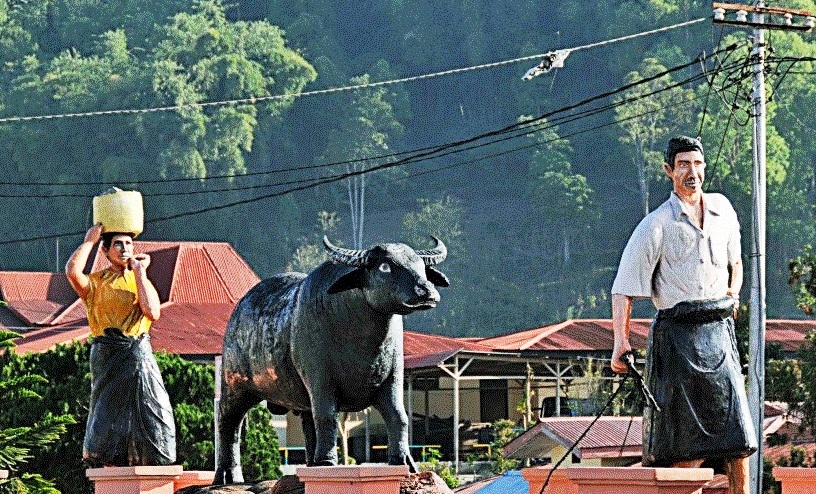
Foto ilustrasi: Kompasiana.com
Pengantar
Budaya adalah hal
yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Para antropolog mengatakan bahwa
budaya merupakan ciptaan manusia dan manusia juga adalah produk budaya. Budaya adalah ciptaan manusia karena memang
ia dihasilkan oleh manusia dalam
relasinya dengan sesama dan lingkungan. Manusia adalah produk budaya karena
manusia lahir dan dibesarkan selalu dalam budaya atau konteks masyarakat
tertentu. Dengan demikian, seluruh hidupnya sudah pasti dipengaruhi oleh budaya
di tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.
Budaya berhubungan dengan
nilai. Nilai itu terungkap dalam ekspresi budaya dalam kehidupan masyarakat.
Antara nilai dan ekspresi budaya itu bisa saja muncul ketegangan. Ketegangan
muncul ketika ekpresi budaya tidak mencerminkan dan mengungkapkan nilai-nilai
yang terkandung dalam budaya bersangkutan sebagaimana diwariskan oleh nenek
moyang.
Ketegangan di atas hemat saya tampak
juga dalam praktik belis yang terjadi di Manggarai saat ini. Jika kita
mengamati dan memperhatikan secara serius, praktik belis di Manggarai saat ini menunjukkan
adanya anomali yang mungkin sulit diatasi. Ekspresi budaya ini dalam
kenyataannya menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai awal yang hendak
diungkapkan dari budaya itu sebagaimana diwariskan oleh nenek moyang. Perempuan
seringkali diperlakukan seolah sebagai barang dagangan yang standar harganya
ditetapkan dengan tegas tanpa kompromi. Praktik semacam itu tak jarang
mendapatkan pembenaran karena didasari oleh alasan sebagai bentuk penghormatan
terhadaap martabat perempuan. Pertanyaannya, benarkah hal itu sebagai
perwujudan penghormatan terhadap martabat perempuan? Ataukah ada suatu
penyimpangan yang terselubung di baliknya yang mungkin kurang disadari?
Manusia dan Barang Dagangan
Saat kita berbelanja di tokoh, kita akan menemukan
sejumlah barang dengan harganya masing-masing. Untuk bisa mendapatkan barang-barang
itu, kita harus membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sesuai dengan harga
barang yang kita mau beli. Setiap barang memunyai standar harganya
masing-masing. Standar itu sudah ditetapkan oleh pemiliknya berdasarkan
pertimbangan untung-rugi. Kalau saja terjadi tawar-menawar saat proses
transaksi, mustahil pemilik tokoh itu menetapkan harga di bawah standar yang
ada, karena jika demikian maka ia akan rugi dan usahanya sudah pasti bangkrut.
Hal ini akan selalu berlaku kapan dan di mana pun. Sebab hukum pasar berlaku di
mana-mana, yakni “mengejar keuntungan sebesar-besarnya”. Membalikan hukum ini
berarti membiarkan bisnis hancur dan mati.
Dalam dunia bisnis, setiap barang selalu punya harga. Untuk suatu yang
punya harga selalu ada alternatif untuk menggantikannya. Misalnya kita hendak
membeli “rinso” di tokoh, tapi ternyata persediaan rinso habis; kita bisa
membeli “daia” atau detergen lain sebagai penggantinya. Selain itu,
barang-barang yang punya harga tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Ia baru
bernilai sejauh berhubungan dengan manusia yang menghasilkan dan menggunakannya.[1]
Rinso misalnya tidak punya nilai dalam dirinya sendiri. Ia baru bernilai sejauh
dihubungkan dengan manusia yang menghasilkan dan menggunakannya. Nilai itu
adalah nilai guna. Nilai ini tidak melekat dalam rinso itu sendiri. Ia selalu
dihubungkan dengan manusia yang menghasilkan dan memanfaatkannya. Itu berarti,
pada tataran tertentu, nilai merupakan hasil konstruksi (budaya) manusia.
Berbeda dengan barang-barang dagangan di pasar, manusia adalah makluk yang
bernilai bagi dan dalam dirinya sendiri. Dalam terang pemikiran Kristen,
manusia adalah ciptaan yang paling istimewah dari segala ciptaan lainnya. Ia
memiliki martabat yang tak dapat ditukar oleh barang apa pun. Martabat itu
melekat dalam dirinya semata-mata karena ia manusia. Hukum atau budaya apa pun
tidak bisa mencabutnya, karena ia melekat dalam kemanusiaan manusia. Dengan demikian,
martabat luhur manusia itu merupakan suatu kualitas yang tak tergantikan dan
tak dapat dihapus oleh kategori apa pun, termasuk kategori budaya. Ia sudah
selalu berada bersama dengan adanya manusia.
Belis dan Martabat Manusia
Coba kita sejenak melihat
praktik belis yang terjadi di Manggarai saat ini. Di beberapa wilayah kita akan
sulit membedakan antara belis yang sesunguhnya sebagaimana diwariskan oleh
nenek moyang kita dan praktik “jual-beli manusia” yang terselubung. Hal itu
tampak dalam kenyataan penetapan standar belis yang mengikuti pendidikan,
pekerjaan, dan kelas sosial orangtua atau keluarga di tengah masyarakat. Hukum
yang berlaku biasanya ialah semakin tinggi pendidikan, pekerjaan, dan kelas
sosial orangtua atau keluarga besar dari mempelai wanita semakin tinggi pula
belis yang mesti dibayar oleh mempelai laki-laki. Bahkan yang menarik ialah
tuntutan itu harus dilunasi oleh mempelai laki-laki. Jika tidak, perkawinan
bisa saja dibatalkan. Hal ini barangkali tidak terjadi untuk kebanyakan
keluarga yang masih sadar akan nilai-nilai hakiki belis yang diwariskan oleh
nenek moyang. Akan tetapi, mesti diakui bahwa fenomena seperti itu ada dan
sedang terjadi.
Praktik belis seperti digambarkan di atas hampir
menyerupai transaksi barang-barang dagangan di pasar. Dalam dunia pasar atau
bisnis kita mengenal hukum ini: “semakin tinggi kualitas barang, semakin mahal
pula harganya”. Jadi, harga barang bergantung pada kualitas barang bersangkutan.
Di sini pertimbangan psiko-emosional, afeksi, cinta, relasi, sosial, kultural
dan martabat tidak muncul, karena memang hal-hal semacam itu tidak ada pada
barang-barang. Hanya manusia sebagai
“individu yang memasyarakat dan masyarakat yang mengindividu serta sebagai
makluk yang tersusun atas kesatuan harmonik jiwa-raga-lah” yang memiliki
hal-hal semacam itu. Di sinilah letak perbedaan manusia dan bukan manusia.
Manusia memiliki martabat, sedangkan barang-barang tidak.
Martabat manusia merupakan suatu yang secara niscaya ada pada manusia. Ia
melekat dalam diri manusia semata-mata karena ia manusia. Hal itu membawa serta
konsekuensi bahwa setiap orang pertama-tama mesti dihargai sebagai manusia terlepas dari kategori dia sebagai laki-laki
atau perempuan, orangtua atau anak-anak, berkulit putih atau berkulit hitam,
dll. Dengan demikian, pola relasi atau budaya apa pun mesti selalu berpegang
pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Perendahan terhadap
martabat manusia justu terjadi ketika manusia diperlakukan sama seperti
barang-barang, binatang atau yang bukan manusia.
Dalam hubungannya dengan budaya belis, pertanyaan yang
muncul ialah, apakah benar belis merupakan perwujudan penghormatan terhadap
martabat perempuan sebagai manusia? Jawabannya bisa “ya” dan bisa “tidak”. Hal
itu tergantung ekspresi budaya itu dalam praktiknya di tengah masyarakat. Belis
menjadi perwujudan penghoramatan terhadap martabat perempuan apabila ekspresi
budaya itu dalam praktiknya tidak menyerupai transaksi barang dagangan di
pasar. Sebaliknya ia bukanlah perwujudan penghormatan terhadap martabat
perempuan ketika ekpresi budaya itu menyerupai transaksi barang dagangan di
pasar. Dalam konteks ini pemaksaan terhadap mempelai laki-laki untuk melunasi
hutang belis agar hubungan sebagai suami-istri antara kedua insan tetap
berlanjut berarti justru merendahkan martabat perempuan, karena perempuan
direduksi menjadi semacam barang dagangan yang standar harganya tidak mengenal
kompromi.
Kita tahu bahwa barang-barang di pasar memunyai standar
harga yang tidak mengenal kompromi bagi para pembeli. Kalau pun ada
tawar-menawar antara pembeli dan penjual, mustahil penjual menetapkan harga di
bawah standar yang ada, karena jika demikian, penjual akan rugi. Apabila uang
pembeli tidak cukup, maka dengan sendirinya ia kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan barang tersebut. Di sini tidak ada kompromi, karena pertimbangan
ekonomis, seperti mengejar keuntungan, menentukan pola relasi antara penjual
dan pembeli.
Hal di atas tentu berbeda dengan pola relasi dalam
perkawinan. Hukum yang terutama dalam perkawinan ialah hukum cinta. Cinta
antara kedua mempelai tidak bisa dibatalkan hanya karena urusan adat tidak
beres. Hal ini tidak berarti bahwa adat itu tidak penting. Adat tetaplah
penting. Akan tetapi, adat itu hanya berfungsi untuk mengesahkan hubungan
antara kedua mempelai secara sosial kultural. Oleh karena itu, keterbatasan
ekonomi dari salah satu mempelai sehingga tidak bisa melunasi hutang belis
misalnya, sama sekali tidak menjadi alasan mendasar untuk membatalkan hubungan
cinta antara kedua insan. Pada titik ini, harus disadari bahwa budaya
diciptakan untuk manusia dan bukannya manusia untuk budaya. Oleh karena itu,
budaya apa pun harus menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap martabat
manusia.
Banyak orang berasumsi bahwa semakin mahal belis untuk seorang perempuan,
semakin tinggi harkat dan martabatnya. Pada titik ini, kita mesti membedakan
harkat dan martabat yang melekat pada manusia sebagai manusia dengan harga diri
sebagai kualitas eksternal manusia yang sangat bergantung pada penilaian
masyarakat. Sebagai suatu kualitas yang melekat secara inheren pada manusia,
keberadaan martabat manusia tidak bisa direduksi kepada penerimaan uang dan
barang materiil oleh seseorang dari orang lain baik melalui suatu hubungan adat
maupun hubungan sosial lainnya. Bahwa pola hubungan itu menentukan
penghoramatan terhadap martabat manusia benar. Namun, tidak benar bahwa pola
hubungan itu menentukan keberadaan martabat manusia. Itu berarti, seorang
dihargai atau tidak di masyarakat, ia tetap memiliki martabat luhur sebagai
manusia. Penghargaan yang diberikan masyarakat tidak menambah atau mengurangi
apa pun pada martabat manusia. Penghargaan yang diberikan hanya bertujuan agar
orang merasa martabatnya tidak dilecehkan atau
supaya orang merasa dihargai sebagai manusia, tetapi tidak menambah apa
pun pada keberadaannya sebagai manusia. Ia tetaplah manusia yang punya esensi
kemanusiaan. Hal ini tentu berbeda dengan harga diri. Harga diri bukanlah suatu
yang esensial pada manusia. Ia tidak berkaitan langsung dengan keberadaan
manusia sebagai manusia. Entah orang dihargai atau tidak dalam masyarakat, ia
tetaplah manusia. Akan tetapi, kita pun tetap dituntut untuk menghargai sesama.
Namun, tidak benar bahwa demi memenuhi kebutuhan akan harga diri dan prestise
sosial kita mengorbankan dimensi-dimensi hakiki pada manusia, seperti dimensi
psikologis, afeksi, cinta, dan lain-lain. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa
mahalnya belis untuk seorang perempuan tidak menambah apa pun pada kualitas
harkat dan martabat manusia (perempuan). Hal itu hanya bertujuan meningkatkan
prestise seseorang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia bisa dikompromi.
Belis: antara Nilai dan Ekspresi Budaya
Belis pada dasarnya merupakan suatu khazanah budaya yang
bernilai. Ia bernilai bukan karena diwariskan secara turun- temurun, melainkan
karena ia bernilai maka ia selalu diwariskan dari generasi ke generasi.
Kesadaran akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menuntut masyarakat kita
untuk tetap melestarikan budaya itu. Tanpa kesadaran itu, budaya belis pasti
sudah ditinggalkan sejak dulu, karena tidak ada gunanya orang melestarikan
suatu yang tidak punya nilai dan makna bagi kehidupan masyarakat.
Budaya selalu berhubungan
dengan nilai-nilai. Karena belis memunyai nilai-nilai maka ia layak disebut
budaya. Budaya tanpa nilai dalam arti tegas bukanlah budaya, melainkan
kebiasaan semata. Belis memiliki sejumlah nilai yang membuatnya layak disebut
budaya dan karena itu pantas untuk dilestarikan. Nilai-nilai itu misalnya,
nilai kekeluargaan, nilai gotong-royong, nilai tanggung jawab, nilai
kemanusiaan, nilai perjuangan, nilai kesetiaan dan pengorbanan, dan lain-lain.
Bertolak dari kerangka penjelasan di atas, yang paling penting dari belis
adalah nilai-nilai adat yang hendak diungkapkanya dan bukannya uang dan
barang-barang materiil yang hendak dibawah. Uang dan barang-barang materiil
hanyalah sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai itu. Maka, akan menjadi terbalik
tatkala kita mengedepankan uang dan barang-barang dari pada nilai-nilai yang
diungkapkannya. Itu berarti uang dan barang-barang materiil tidak perlu
berjumlah sangat besar sampai-sampai menimbulkan hutang baru bagi keluarga
mempelai laki-laki. Selain itu, tidak perlu ada pemaksaan yang melampaui
kemampuan ekonomis keluarga mempelai laki-laki. Apalagi kalau pemaksaan itu
berujung pada pembatalan hubungan kedua mempelai. Hal ini jika terjadi berarti
ekspresi budaya kita menyerupai hukum pasar dan dengan sendirinya budaya itu
kehilangan nilainya yang luhur, karena manusia justru menjadi objek dari budaya
yang diciptakannya. Padahal, ekspresi budaya itu bisa disesuaikan dengan situasi
dan kondisi yang ada asalkan ia tidak kehilangan nilai-nilainya. Itu berarti
yang penting adalah pembicaraan adat atau meja adat bukan barang-barang
material dan uang. Dalam kebudayaan Manggarai dikenal istilah rojo wae nelu. Rojo wae nelu tidak menyerupai pola relasi di dunia bisnis.
Hubungan yang terjalin dalam rojo wae
nelu bukan hubungan yang langsung berakhir, melainkan hubungan yang akan
terus berlanjut. Mengapa demikian? Karena rojo
wae nelu menyingkapkan komunikasi manusia dengan manusia dan bukan manusia
dengan binatang. Karena komunikasi itu melibatkan manusia dengan manusia, maka tidak
ada yang ditempatkan sebagai objek. Keduanya sebagai subjek. Uang, barang
material, dan binatang bisa saja menjadi sarana simbolis untuk mengungkapkan
nilai-nilai dalam komunikasi itu, tetapi manusia tidak pernah menjadi
objek.
Penutup
Belis tetaplah suatu warisan budaya
yang bernilai. Kesadaran ini mendorong setiap generasi untuk mewarisinya secara
turun-temurun. Dalam proses pewarisan itu, ekspresi budaya untuk mengungkapkan
nilai itu bisa saja berubah, tetapi nilai-nilainya tetap atau ditambahkan,
tetapi tidak boleh dikurangkan. Namun, hal yang penting diperhatikan ialah,
ekspresi budaya apa pun bentuknya mesti menjunjung tinggi pernghormatan terhadap
martabat manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia mengandaikan manusia
selalu ditempatkan sebagai subjek dari budaya dan bukannya objek yang
diperlakukan sama seperti barang-barang dagangan di pasar.
[1]
Pandangan ini berlaku untuk
barang-barang yang dihasilkan oleh manusia untuk kepentingan atau kebutuhan
kelangsungan hidupnya dan bukan untuk realitas ciptaan yang menurut Kitab
Kejadian telah diciptakan baik adanya.
KETIKA MANUSIA MENJADI BARANG DAGANGAN (Catatan atas Anomali Praktik Belis di Manggarai)
![KETIKA MANUSIA MENJADI BARANG DAGANGAN (Catatan atas Anomali Praktik Belis di Manggarai)]() Reviewed by insancerdaspolitik
on
August 01, 2018
Rating:
Reviewed by insancerdaspolitik
on
August 01, 2018
Rating:





No comments: